Rabu, 22 Oktober 2008
Kembali ke Pedesaan dan Pertanian, Sebuah renungan dari pidato seorang Guru Besar
Hadirin yang saya muliakan,
Nyaris tidak lagi terdengar ungkapan Gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem
kerta raharja. Kiasan sang Pujangga (Anonim, 1941), yang dulu acap terdengar dalam
antawacana ringgit purwa di Balai Desa, telah mempengaruhi pikiran seorang anak
desa yang hidup dari langgar ke langgar, jauh dari hingar bingar kota. Pengaruh tersebut
diperkuat sumpah serapah kaum ibu ketika jengkel terhadap putri nakalnya sembari
sepata: ”tak dongakke mbesuk gedhe entuk bojo pegawai kowe ndhuuk..”.
Tersirat hebatnya potensi pedesaan dan pertanian tempo doeloe, ketika Nusantara
masih meyakini diri sebagai Negara Agraris. Keyakinan itulah landasan prioritasi yang
tersurat dalam langkah keagrariaan sejak proklamasi 1945, dan ditopang berbagai
lembaga teknis pembangunan pedesaan dan pertanian yang dipandang sebagai soal
hidup atau mati (Soekarno, 1952). Semangat prioritasi ini secara substantif-revolusioner
mulai dirancang melalui dibentuknya Panitia Agraria Jogjakarta, 1948.
Semangat agraris tersebut tak pernah luntur. Misi Panitia Jogja berurutan
dilanjutkan Panitia Agraria Djakarta, 1951, dan Panitia Soewahjo, 1955, disusul
lahirnya Rancangan Soenarjo, 1958, Rancangan Soedjarwo, 1960, dan disahkannya
Undang-Undang Pokok Agraria (UU-5/1960) yang diundangkan dalam Lembaran
Negara no. 104, 24 September 1960 (Harsono, 1968). Kedaulatan ekonomi jutaan
investor gurem adalah esensi utama UUPA, yang ditegaskan dalam konsideran Keppres
RI No. 169/1963 tentang Penetapan 24 September sebagai Hari Tani:
Bahwa tanggal 24 September, hari lahirnja Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hari
kemenangan bagi Rakjat Tani Indonesia, dengan diletakkannja dasar-dasar bagi penyelenggaraan land reform untuk mengkikis habis sisa-sisa imperialisme dalam lapangan pertanahan, agar rakyat tani dapat membebaskan diri dari segala matjam bentuk penghisapan manusia atas manusia dengan beralat tanah, sehingga melempangkan jalan menuju ke arah masyarakat adil dan makmur.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Dibentuknya Kementerian Pembangunan Masyarakat, dipimpin Soegondo, 1950,
merupakan pendekatan sosial yang dipilih, menyertai upaya teknis. Pelembagaan
pembangunan masyarakat desa mewarnai pula tata-lembaga seluruh konfigurasi politik
nasional (Haryati, 2003). Yang menarik adalah temuan Haryati bahwa semua itu gagal
membangun kemandirian dan ketahanan rakyat. Kalau pada masa awal usia bangsa,
kegagalan itu karena persoalan politik sebagai negara baru, pada masa terakhir justru
karena pembangunan menempatkan rakyat sebagai instrumen, alat pembenar dan
legitimasi belaka. Menempatkan mereka sebagai obyekpun Negara, tepatnya
Pemerintah, telah gagal, apalagi sebagai subyek pembangunan (Maksum 2005).
Instrumentalisasi rakyat mengingkari dua asas dari Panca Program UUPA
(Harsono, 1968) yaitu penghentian penghisapan feodal terhadap rakyat dan perencanaan
tata-agraria. Dua asas yang belakangan disebut access reform adalah pasangan land
reform dalam UUPA, dan berkenaan dengan reforma akses yang memungkinkan rakyat
memanfaatkan lahan lebih baik sebagai alat ekonomi, termasuk akses partisipasi, modal,
teknologi, pasar, informasi, dsb. (Winoto, 2007). Ironisnya, akses yang seharusnya
dibuka luas bagi pedesaan, pertanian dan agro-industri Negara agraris ini justru dibuntu
dalam gegap-gempita industrialisasi.
Pedesaan dan pertanian, kendati sangat berbeda, memiliki kepaduan sektoral yang
nyaris tak terpisahkan. Kembali ke Desa (KkD) dan pengawinan kata pedesaan dan
pertanian dalam pidato ini dimaknai sebagai ’pertanian pedesaan’, pertaniannya rakyat
tani sebagai jutaan investor gurem dan subyek dengan segala kedaulatannya.
Segmentasi ini dibuat karena instrumentalisasi telah memupuk subur ketergantungan
dan ketidakberdayaan petani, pembahasaan lain ungkapan Haryati (2003): kegagalan
pengembangan kemandirian dan ketahanan rakyat pedesaan, sebagai beban historis
monumental pembangunan pertanian.
Beban Historis
Dalam prosesi kepemimpinan nasional, pemerintahan masa reformasi tidak
terlepas dari persoalan pembangunan rejim sebelumnya yang mengikat sebagai kendala.
Sedikitnya ada tiga kendala ekonomi-politis merupakan beban sejarah struktural yang
membatasi kinerja dan akselerasi pembangunan pertanian sebagai salah satu pilar
perekonomian bangsa (Maksum, 2004a).
Pertama, kegagalan adopsi model pembangunan dalam pengembangan pedesaan
dan pengentasan kemiskinan. Tanpa menafikan capaian positif yang ada,
pengembangan pedesaan dalam semua konfigurasi politik menanamkan ketergantungan
dan ketidakberdayaan publik sebagaimana disebutkan. Kegagalan adopsi nilai asasi
participation-creativity-stimulation dalam pemberdayaan, adalah pelajaran mendasar
yang seharusnya telah dibenahi lebih awal dalam masa pemerintahan pasca Orde Baru.
Berpuluh tahun, pembangunan dilakukan sentralistik dan otoriter dengan Negara
sebagai pusat kekuatan ekonomi (Mas’oed et.al., 2000; Jung, et.al., 2003). Reformasi
menuju desentralisasi dan otonomi daerah ditandai oleh maraknya gagap kolektif pada
semua level dan diwarnai euphoria politik, politik lokal dan politik aliran, serta
partisipasi publik plintiran. Ini semua adalah beban historis kedua anak bangsa yang
hampir sepuluh tahun reformasi tetapi tanpa realisasi, karena tidak pernah bertemunya
gerakan politik dan pembangunan perekonomian (Joesoef, 2007), serta makin
gentayangan-nya hantu-hantu demokrasi (Piliang, 2007).
Beban ketiga adalah krisis ekonomi yang terjadi akibat kebablasen mengimani the
Asian Development Model dengan Negara sebagai kekuatan sentral industrialisasi dan
menempatkan pertanian termarjinalisasi. Agro-industri yang sebetulnya mudah
berkembang keunggulan kempetitifnya karena telah dimilikinya keunggulan komparatif
dan seharusnya dipilih dalam industrialisasi, justru tidak dikembangkan dan malah
dikorbankan untuk industri non-pertanian. Rehabilitasi sektor pertanian tentu bukan
tugas yang mudah, setelah beberapa dekade dikorbankan kecuali untuk beras, dan
setelah NKRI terjun bebas, masuk kelompok negara melarat kurang pangan, the Low
Income Food Deficit Countries (LIFDCs) menurut FAO (Ismoyowati and Maksum,
2002; Jung, et.al., 2003).
Industrialisasi yang menganaktirkan agro-industri ini telah gagal total dan menjadi
biang terjerumusnya Bangsa ini dalam krisis sepuluh tahun lalu (Jung et. al., 2003).
Sementara itu, progres pertanian hanyalah produksi beras, yang menebar banyak
patologi pedesaan, a.l.: (i) orientasi produksinya memiskinkan petani; (ii) tiadanya
insentif pengembangan komoditas non-beras; (iii) ketergantungan lahan terhadap bahan
kimiawi; (iv) menyalah-artikan ketahanan pangan; (v) stagnasi diversifikasi usahatani;
dan (vi) ketahanan pangan makin tergantung beras, menafikan keragaman lokal
(Kuswanto and Maksum. 1999).
Bukanlah apologi kalau beban historis ini diulas sehingga rakyat terpaksa harus
memaklumi kegagalan, sementara Pemerintah boleh berlamban diri. Bukan pula untuk
menafikan masalah lain, di luar tiga kendala dimaksud. Hal ini semata diulas guna
memperkaya obyektifitas dalam memahami dan mengkritisi kinerja sektoral pedesaanpertanian
pasca Orba, dan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pada khususnya, sekaligus
untuk membangun landasan kebijakan pertanian pedesaan dan perekonomian bangsa ke
depan menghadapi tantangan global.
Hadirin yang saya muliakan,
Tantangan Global Climate change yang ramai dirembug dalam Konferensi Para Pihak ke-13 (COP-13) di Bali dan dihadiri ribuan peserta berikut sejumlah kesepakatan yang dihasilkan,
memiliki banyak makna bagi sistem pangan global, pertanian dan lingkungan.
Pergeseran dan ketidakpastian musim berakibat menguatnya tekanan pasar pangan,
ditengarai naiknya harga pangan dunia. Inilah tekanan global pertama, yang jauh
sebelum Konferensi, telah diperingatkan oleh banyak pihak bahwa pertanian akan
menjadi sektor yang paling terpukul (Harijono dan Isworo. 2007).
Kedua, pergeseran manfaat komoditas pertanian menjadi sumber energi nabati,
suka atau tidak suka, akan mengakibatkan tajamnya konflik pemanfaatan lahan yang
mengancam produksi pangan bagi 230 juta jiwa lebih manusia Indonesia (Fujita, 2007).
Bagi tokoh LIFDCs seperti Indonesia, global shock ini adalah persoalan pembangunan
yang harus lebih serius dicermati. Krisis pangan negeri agraris sekarang ini adalah
lampu merah yang bisa membenamkannya lebih jauh lagi dalam LIFDCs.
Perkembangan politik pertanian global tidak kalah kuatnya sebagai tekanan ketiga
bagi Indonesia. Ketika wacana dunia yang didominasi wacana the end of ideology (Bell,
1960; Fukuyama, 1989; 1992), peringatan Blank (1998) tentang kiamatnya pertanian,
dan apatisme pertanian negara maju (Ikerd, 2001), dimentahkan habis oleh September
bombing 2001 yang meluluh-lantakkan twin towers, terbelalaklah mata dunia maju akan
kerentanan bangsanya terhadap sabotase dan teror. Kesadaran yang berubah menjadi
kewaspadaan terhadap terorisme, dan kemudian memilih proteksi pangan sebagai
urusan ketahanan nasional, cukup menggetarkan negara berkembang yang agraris.
Dicontohkan oleh Brown (2003), bahwa Amerika langsung membentuk
Department of Homeland Security (DHS), 2 Juni 2002, sebagai proteksi. Bush yakin
kalau pertanian dan pangan amat rentan bio-terrorism dan percaya bahwa homeland
security dipengaruhi pertanian yang punya relasi kuat dengan kesehatan ekonomi dan
national security (Dreyfuss, 2004). Kalau Soekarno (1952) menyebut pertanian soal
hidup atau mati, Bush melihat agricultural and food security sebagai pilar national
security. Puncaknya, Homeland Security Presidential Directive HSPD-9, yang
perihalnya adalah Defense of United States Food Purpose, diundangkan oleh the White
House (2004), 30 Januari 2004.
Pola nalar Blank (1998) telah lebih lama menjangkiti teknokrat kita yang disetir
para ekonomis dalam perencanaan Negara. Mereka berpikir amat korporatis dan
liberalistis. Fenomena ini menyesatkan kiblat Bangsa, karena pertanian dilihat hanya
sebagai fenomena ekonomis semata dan urusan pilihan, bukan urusan wajib. Yang
sebenarnya terjadi adalah mereka telah gagal telah memahami what is in a grain of rice,
meminjam judul buku 80an. Tentu, kata rice dipakai untuk menyebut pertanian dalam
pengertian luas dan multidimensional.
Menguatnya proteksi negara maju membuat makin tidak adilnya perdagangan
dunia. Ketidakadilan liberalisasi yang belum selesai, masih tetap merupakan ancaman
global yang dihadapi negara berkembang. Kegagalan beberapa putaran persidangan
WTO menunjukkan bagaimana negara berkembang anggota lembaga ini tidak bisa
menerima proteksi negara maju yang makin berlebihan terhadap sektor pertaniannya.
Keengganan negara maju untuk menurunkan proteksi ini adalah jalan buntu.
Empat persoalan tersebut adalah tekanan global dan eksternal terhadap pertanian
Indonesia, terutama ketika berada dalam ketergantungan import yang tinggi. Tetapi sulit
dipahami kalau para petinggi justru pesimis, menderita gagap kolektif, dan cenderung
meden-medeni. Tidak jelas, itu pesimisme atau rekayasa mereka yang terlanjur cinta
impor pangan dengan janji upeti, meski kedaulatan pangan tergadaikan (Maksum,
2007a). Pesimisme itu ketemu sikap petinggi yang tawadlu’, sami’na wa atho’na,
mengimani firman World Bank (WB) yang memang telah lama dipertuhankan, meski
romantisme pangan murah menuntut konsekuensi dlalimisasi rakyat tani.
Hadirin dan hadirat, rohima kumullah
Tekanan global yang bermuara pada empat hal tersebut memang merupakan
ancaman ketika tidak disadari bahwa negara ini sebetulnya sudah lama ’bunuh diri’
dengan memupuk import dependency, sehingga setiap gangguan impor adalah ancaman.
Berbeda kalau pola pikir dirubah dari raja impor ke pola pikir agraris. Dalam posisi
agraris NKRI akan memandang tekanan dunia bukan lagi ancaman, tetapi tantangan,
optimisme baru dan peluang (Maksum, 2007c), seperti optimisme swasembada dan anti
import Presiden yang dilontarkan di Bandar Lampung dalam Peringatan Hari Pangan
se-Dunia, 5 Desember 2007.
Importasi dan eksportasi memang hal wajar dan saling menguntungkan dalam
perdagangan internasional. Begitulah dogma konvensionalnya. Akan tetapi, dalam
dunia yang sarat politisasi, global trading tidak bisa dibatasi sekedar sebagai urusan
finansial. Tidak cukup pula dibatasi nalar ekonomis. Tetapi harus lebih luas dan
meliputi urusan ekonomi politik, political ecology, welfare economics dan justice issues
(Robbins, 2004; Maksum, 2007c).
Komplikasi importasi ini ditunjukkan dengan jelas oleh gonjang-ganjing tahutempe
awal 2008 akibat syahwat pejabat memupuk import dependency kedele, terlebih
setelah Indonesia diamputasi IMF, 1998, serta terbius harga dunia yang murah dan
kredit import dengan bunga nol persen, berikut segala rentenya, 1999-2002. Potensi
produksi nasional yang 15 tahun lalu swasembada dengan produksi 1,8 juta ton tertutup
birahi jangka pendek. Akibatnya, produktifitas nasional merosot tajam menjadi 620.000
ton pada tahun 2007 (Deptan, 2007), setelah sebelumnya 748.000 dan 808.000 ton pada
tahun 2006 dan 2005. Betul sekali bahwa panasnya tahu-tempe ini adalah gejala global.
Namun demikian, tergantungnya kinerja sistem ketahanan pangan telah mengakibatkan
gejala global tersebut terasa berlipat ganda. Konsistensi kebijakan sungguh amat
dibutuhkan, bukannya ketidakpastian, dan keasyikan dendang ria: esuk tempe sore dele.
Gambaran importasi yang sering terbius oleh legitimasi ilusi finansial publik dan
dibangun dengan membesar-besarkan isu price discrepancy antar negara seperti
dicontohkan dalam krisis tahu-tempe, sering pula memperoleh pembenaran akademisi
tukang, walau berimplikasi marjinalisasi sektoral fatal. Apa yang terjadi dalam industri
pangan, khususnya perberasan nasional, memberikan ilustrasi lebih lengkap bagaimana
ilusi dibangun guna menghasilkan keputusan yang dikotomis, merugikan rakyat tani,
dan keberlanjutan sistem ketahanan pangan domestik.
Dikotomi Ekonomis Inflasi 8,7% untuk Oktober 2005, menyusul kenaikan harga BBM, sangat
mengejutkan para petinggi yang takut inflasi tahunan dua digit. Dalam gagap kolektif,
pengendalian kuat harga beras dan gula dinyanyikan sebagai solusi. Dalihnya, daya beli
publik terbatas. Importasi beras semakin bertubi-tubi meski selalu dalam kontroversi.
Amanat pengendalian inflasi Presiden waktu melantik reshuffle kabinet, Desember
2005, dianggap restu terhadap modus operandi yang telah diputuskan para menteri.
Naasnya rakyat tani dalam inflasi, harga beras tidak boleh naik meski dia hanyalah
komponen dan transmitter, bukan penyebab inflasi, yang memang dipicu BBM. Pada
saat yang sama, petani juga pelengkap penderita dalam pengurangan subsidi BBM yang
didukung LPEM-UI dan 26 tokoh nasional. Dukungan berbasis ramalan akan turunnya
angka kemiskinan menjadi 13,87% karena kompensasi BBM ini sangat disesalkan
Mubyarto (2005) dalam tulisan terakhirnya. Ternyata, kemiskinan menjadi 17,75%
setahun kemudian, Februari 2006 (Anonim, 2007a), menjelang khaul pertama
Almarhum Pak Muby. Penghujung 2006 kembali diwarnai firman WB akan perlu dimurahkannya beras. Menurut lembaga pelepas uang ini, kenaikan harga beras telah menyebabkan tambahan tiga juta lebih orang miskin dan naiknya angka kemiskinan dari 15,97%, Maret 2005,menjadi 17,75%, Februari 2006. Amanat akhirus sanah itupun ditunjang dramatisasi WB tentang angka kemiskinan 49% kalau dipakai garis kemiskinan US$ 2,-, dan masih dibumbui firman akademik WB awal 2007 bahwa HET beras sebesar Rp 4.000,-per
kilogram, dengan HPP, Harga Pembelian Pemerintah, yang tak perlu dirubah, sesuai
Inpres 13/2005 (Anonim, 2007a).
Sekilas, fakta di atas telah menggambarkan siapa penentu kebijakan pangan
nasional sekaligus ashbaabul mushibah, biang kemandegan sektor pangan karena
ilustrasi itu menunjukkan adanya dua beban sektor pertanian: sebagai produsen pangan
murah dan pengendali inflasi, meskipun hakekatnya persoalan harga dan inflationarynya
perekonomian dipicu oleh kenaikan harga BBM. Sementara itu, pada sisi
permintaan, rendahnya daya beli sebagai kambing hitam, sebenarnya terjadi akibat
gagalnya membuka lapangan kerja sehingga pertanian menjadi bemper tenaga kerja.
Bemper ketenagakerjaan ini adalah beban ketiga.
Sofistikasi romantisme beras murah berdalih bahwa rakyat tani adalah net
consumers (Anonim, 2007a). Dalih yang selama ini dibesar-besarkan WB ternyata
dibantah Arifin (2007). Inpres 3/2007 yang harapannya memperbaiki nasib rakyat tani
juga tidak jelas karena ’amanat’ bahwa beras harus lebih murah dari gabah, satu kondisi
yang tidak pernah terjadi sejak Mahapatih Gadjah Mada masih sugeng. Melengkapi
romantisme, kembalinya paket monopoli impor beras September 2007 (Maksum,
2007c), plus kado tahun baru penurunan tarif impor beras 18,2% menurut PMK:
180/PMK.0111/2007 (Kompas 2007c), telah menambah deretan kepiluan struktural
rakyat tani produsen beras.
Akibat romantisme, petani yang sudah miskin harus ikhlas untuk lebih miskin
lagi, menerima harga murah supaya tetangga yang daya belinya terbatas bisa makan
(termasuk dosen, guru besar, tentara, dll.?). Padahal, menurut pemetaan KIKIS (2000)
di tujuh vocal points, termasuk vocal point petani sawah oleh PSPK-UGM dan PERCIK
(Maksum and Arif, 2001; 2002; Maksum, 2004b), lemahnya daya beli ini bersifat
struktural. Adalah tanda tanya besar, mengapa lemahnya daya beli karena kemiskinan
struktural tidak diatasi dengan pragmatisme fiskal dan special policy, tetapi melalui
common policy dengan memurahkan beras yang accessible bagi siapa saja. Bahaya
sekali dogma WB yang tidak berbasis perbaikan daya beli dalam mengatasi kemiskinan,
tetapi dengan memurah-murahkan pangan dan melanggar prinsip indivisibility of human
right-nya UNDP (2005).
Pembenaran lain importasi adalah rendahnya produktifitas, dan efisiensi domestik,
serta murahnya impor. Semua ini tentu harus komprehensif komparasinya karena terkait
beragam hal, mulai tingkat mikro, sampai supra makro: capital cost, export subsidy,
trade policy, monetary dan fiscal policies, internal dan eksternal (Maksum, 2007c).
Andai saja rupiah tidak diproteksi dengan Rp 18 Triliun, 2005 dan Rp 20 Triliunan,
2006 (Kompas, 2006), yang tiga kali dana Deptan, rupiah akan membalik kita jadi
eksportir. Kajian komprehensif, internal dan external antar-negara belum pernah
dilakukan kecuali komparasi sulapan.
Hadirin yang saya muliakan
Itulah yang terjadi pada sub sektor pangan. Melalui tinjauan empiris yang
dilakukan Maksum (2006) disimpulkan bahwa semrawutnya subsektor pangan cukup
mewakili sektor pertanian secara keseluruhan, termasuk peternakan, perikanan,
kehutanan, dan keagrariaan. Dampak proteksi rupiah misalnya, berakibat semakin
mahalnya beaya produksi dan melemahnya daya saing sektor pertanian yang memang
sarat dengan domestic contents.
Penghapusan BUSEP, kewajiban pabrik menampung susu lokal, telah merugikan
peternak sapi perah (Maksum, 2004c). Impor daging sapi gendheng, telur busuk dan
paha ayam, juga membunuh peternak. Perikanan-kelautan yang telah lama dianaktirikan,
belum punya kemajuan berarti. Proteksi nelayan yang tak jelas, Over-fishing,
illegal fishing, maraknya trawlers asing, dan kedaulatan pulau kecil yang rawan okupasi
asing adalah raport perikanan. Sementara, saktinya cukong illegal logging, konservasi
yang tidak mensejahterakan petani, degradasi daerah tangkapan air, dan makin
haramnya kerajinan kayu spanyolan, adalah sebagian kecil dari prestasi kehutanan.
Sederet kepiluan itu masih ditambah agricultural injustice hasil pemetaan PSPKUGM
dalam kajian Access to Justice (A2J) dengan dominasi kasus konflik pemilikan
lahan di luar Jawa yang terjadi: (i) antar individu rakyat tani; (ii) antar komunitas petani;
(iii) antara petani dengan pemilik modal; dan (iv) antara petani, individu atau kelompok,
dengan Negara yang kinerja agrarianya masih jauh dari harapan UUPA (PSPK and
UNDP, 2006).
Hadirin yang terhormat,
Dari beberapa ilustrasi, bisa disimpulkan bahwa semua itu terjadi karena kebijakan
pembangunan teramat dikotomis, menempatkan pertanian yang potensial bagi agroindustrialisasi,
dianak-tirikan sebagai sesaji pemanjaan sektor industri non-agro, dengan
fungsionalisasi pertanian sebagai: (i) pengendali inflasi, (ii) penyedia bahan baku
murah, (iii) produsen pangan murah; (iv) tumbal ketahanan pangan; dan (v) bemper
ketenagakerjaan.
Kebijakan pembangunan yang meletakkan sektor pertanian sebagai prioritas dan
leading sector dalam dokumen legal saja, seperti Repelita, GBHN-GBHN, Propenas,
sampai RPPK, sudah barang tentu merupakan structural injustice yang tidak bisa
dipahami. Karenanya, cermat sekali bagi pimpinan nasional yang memang dimulai dari
desa dengan janji-janji kepada rakyat tani, jikalau KkD, membangun konsistensi janji
kampanye dengan realisasi. Itu kalau tidak ingin terjadi pengorbanan rakyat dan
pencemaran kepemimpinan nasional oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab sehingga
memenuhi sindiran Suswono (2007) bahwa revitalisasi tidak pernah maksimal dan
sekedar retorika. Ma’asyiral hadlirin wal hadliraat, rahima kumullah,
Kembali ke Desa
Dikorbankannya sektor pertanian-pedesaan-tradisional vis-a-vis sektor industriperkotaan-
moderen akhirnya menempatkan industri non-pertanian paling diuntungkan
karena pangan dan tenaga kerja murah. Akibatnya, profitabilitas artifisial bisa dibangun
semena-mena (Maksum, 2007c) dengan rakyat tani sebagai the most disadvantaged
people (PSPK and UNDP, 2006). Masih memadai kalau protected business ini berubah
dari infant industry jadi dewasa dan berdaya-saing ketika disapih. Nyatanya tidak.
Setelah proteksi, kedirgantaraan malah mundur banyak langkah, telekomunikasi dijarah
Temasek dan Indonesia menjadi users only, pertambangan dan energi makin asyik lego
konsesi, dan industri elektronika, menurut Masykur Wiratmo (2003), didominasi
kemajuan teknologi adopsi, rakitan dan bajakan.
Melihat kegagalan industri pada satu sisi, dan potensi pertanian pada sisi lain,
maka industrialisasi sudah seharusnya menuju agro-industri. Potensi ini tumbuh hebat:
1,3% dari 6,5% pertumbuhan kwartal ketiga (Kompas, 2007b), sumbangan tertinggi
sepanjang sejarah meski dihempas eskalasi BBM dan terkekang beragam kendala
struktural. Hal ini mestinya membuat para pemimpin tersadar untuk melakukan
taubatan nashuha setelah menganak-tirikan pertanian, dan kemudian menebus dengan
membangun kesepakatan baru untuk KkD, pro-pertanian dan rakyat tani, meyakini
kodrat agraris sebagai berkah Ilahiyah.
Pertanian telah menyelamatkan bangsa dengan mendukung pertumbuhan 2007
yang diperkirakan 6,3%, dan ditopang oleh kemantapan produksi pangan domestik.
Tercapainya produksi padi 2007 sebesar 57 juta ton gabah kering giling dengan
pertumbuhan 4,76% (Deptan, 2007) adalah indikasi bahwa swasembada dan anti
importasi yang dicanangkan Presiden awal Desember, bukanlah mimpi siang bolong,
walaupun menuntut konsekuensi: pupusnya rente importasi bagi oknum petinggi.
Hadirin yang dirahmati Allah
Subhaanallah. Dalam Climate change ternyata masih ada berkah Ilahi
peningkatan produksi, meski pusat pertumbuhan tidak lagi di kawasan langganan di
Jawa yang hanya tumbuh 2,24%, dan diwarnai aneka kepalsuan, benih bajakan, pupuk
subsidi yang menghilang, serta segala kelambatan. Pertumbuhan terjadi di luar Jawa
dengan laju 7,8% (Deptan, 2007). Data ini memancing dugaan bahwa kreatifitas lokal
memanfaatkan musim kemarau yang basah adalah penyelamat sistem pangan nasional
kali ini.
Gairah pertanian juga muncul karena dukungannya terhadap industri pengolahan
yang ekspornya bernilai US$ 4.4 Milyar, 2005 dan US$ 5.4 Milyar, 2006 (Idris, 2007).
Kontribusi industri pengolahan non-migas sebesar 27,6% terhadap PDB-2006, 7,16%
milik industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau. Kontribusi paling
signifikan PDB-2006 dari sektor pengolahan non migas didominasi cabang industri
makanan, minuman dan tembakau (27,9%), barang kayu dan hasil hutan lain (5,8%),
dan kertas dan barang cetakan (5,2%). Pertumbuhan subsektor inipun naik tajam dari
2,75% tahun 2005 menjadi 7,22%, tahun 2006.
Optimisme pangan, kontribusi PDB pertanian dan naiknya eksportasi justru hebat
dalam kondisi iklim tidak ramah dan eskalasi harga BBM. Berdasarkan fakta ini
pesimisme para introverts dalam melihat tekanan global, yang melenceng dari tekad
Presiden, mustinya dipermak. Terlebih, mengingat selama ini agroindustri tidak
mendapat dukungan struktural (Prabowo dan Hamzirwan, 2007). Structural adjustment
(Maksum, 2007b) karenanya, memperoleh legitimasi untuk dibangun dan membalik
kiblat pembangunan yang anti-petani menjadi KkD, pro-petani, mendasari optimisme
menatap tekanan sebagai tantangan. Kompetisi global tentu menuntut pendekatan
industrial dalam memuluskan jalan KkD.
Industri Pertanian sebagai Landasan
Ketika kata industri terdengar, asosiasi publik tertuju pada pengolahan bahan baku
menjadi bahan jadi dan setengah jadi, serta terkait dengan sofistikasi rekayasa dan
teknologi seperti pabrik pesawat terbang, TIK, dsb., yang disebut salah kaprah sebagai
industri. Akibatnya, industrialisasi dan industrial society menjadi terkait dengan pabrik,
seutas dasi, teknisi dan para kuli.
Kedirgantaraan pernah menjadi prioritas, disertai proteksi pol-polan industri
otomotif dan elektronika. Semua berbasis import, padat modal dan teknologi.
Konsekuensinya, industri pertanian nasional yang potensial (Idris, 2007), diposisikan
sebagai pelayan. Industrialisasi pertanian tidak pernah dilakukan serius kecuali makin
tak punya masa depan, terutama bagi anak muda dan direspon industri pendidikan yang
ditandai oleh kian jijiknya ABG terhadap ilmu pertanian, pangan, dan pedesaan.
Kata industri dalam dua paragrap terakhir memiliki jarak makna amat lebar. Pada
paragrap terdahulu, dipahami salah kaprah, berasosiasi fabrikasi dan pengolahan bahan.
Sementara, paragrap yang kemudian, tidak harus mensiratkan aktifitas pabrik. Industri
dalam hal ini meliputi pengertian serba cakup seluruh aktifitas sistem industri, yang
memiliki karakter sosio-kultural sesuai dengan word history-nya (Anonim, 2007b) sbb.:
coming from the Latin word industria meaning “diligent activity directed to some purpose,” and its descendant, Old French Industrie, with the senses “activity,” “ability,” and “a trade or
occupation,” our word (first recorded in 1475) originally meant “skill,” “a device,” and “diligence”
as well as “a trade.” Over the course of industrial revolution, as more and more human effort
became involved in producing good and services for sale, the last sense industry and the slightly
newer sense “systematic work or habitual employment” grew in importance, to a large extent
taking over the word.
Mengingat watak sosio-kultural tersebut, maka pengertian industrial society tidak
harus disunat menjadi sekedar pekerja pabrik, permesinan dan berdasi. Dia bisa terkait
dengan urusan sektoral yang sangat primer sekalipun, seperti konservasi dan pertanianpedesaan, selama berorientasi systematic work to some purposes. Sayangnya, kata ini
terkontaminasi kata informatika dan sebagainya, sehingga melupakan pertanianpedesaan,
kearifan dan sain rakyat tani. Adalah dosa besar dogma absolut ekonomi
pembangunan yang melihat pertanian indikasi kemunduran Negara. Dalam kaitan
sosiologis, Gumilar (Kompas, 2007b) mengingatkan bahwa masyarakat industri ditandai
oleh suburnya komunitas dengan sensibilitas, nilai, semangat, dan etos kewirausahaan
sehingga adaptif dan kreatif merespon dinamika dan logika ekonomi pasar.
Mencermati nalar Gumilar, mestinya nasionalisme kita terusik melihat eksportasi
yang didominasi glondhongan kayu, peresan sawit, klathak kakao, tuna segar, getah
karet, biji kopi, mentahan mete, bijih perak, dan segala mentahan. Sementara, importasi
diwarnai bau sengak starbuck, von houten, bridgestones, dan krisis bahan baku Kota
Gede yang membunuh pengrajin dan ribuan buruh. Krisis industrial sungguh sedang
terjadi, bukan karena faktor teknologis, tetapi karena pola pikir dan kebijakan Negara
yang tidak industrial sehingga melepas larinya peluang nilai tambah dan maslahah lebih
luas yang harusnya bisa dikais melalui industrialisasi pedesaan sampai global tradingnya.
Industrialisasi Pedesaan Sebagai Strategi
KkD dan industrialisasi pedesaan dengan demikian memang persoalan
transformasi sosio-kultural (Maksum et.al., 1999). Oleh karenanya, perjalanan KkD
memerlukan preconditioning berupa segala stimulasi, reformasi insentif dan kebijakan
untuk tidak lagi menganaktirikan pertanian-pedesaan, mulai yang paling mikro melalui
access reform secara konsisten, sampai kebijakan fiskal dan moneter yang berkeadilan
bagi keseluruhan sektor ekonomi.
Sebagai contoh, proteksi rupiah berlebihan yang selama ini dilakukan demi
kelayakan import-based industry, sudah waktunya dihentikan karena menyebar
kesengsaraan melalui pemahalan biaya faktor produksi domestik dan penyebab
disebutnya pertanian tidak efisien, sehingga solusinya adalah importasi dengan segala
implikasi. Banyak lagi kebijakan harus ditinjau ulang karena telah mencederai sektor
pertanian yang sebetulnya hanya menuntut fair play dan dipasangkan sejajar dengan
industri lain, tidak justru semakin dikorbankan dalam dikotomi ekonomis.
Global shock yang dihadapi oleh Bangsa dengan beragam beban historis tentu
memerlukan antisipasi cermat sebuah good governance yang tidak hanya transparan,
akuntable, partisipatif, dsb., tetapi juga harus adil, terutama bagi sang papa, the most
disadvantaged people (Sen, 2003; UNDP, 2005). Sectoral injustice sudah waktunya
diparkir karena sudah tidak njamani dan lebih banyak menyebarkan madlarat daripada
kemaslahatan umat.
Sebagai persoalan sosiokultural, perjalanan KkD senantiasa berbasis
kesetimbangan sistem sosiokultural lokal yang dibatasi kinerja subsistem pendukungnya
(Koentjaraningrat, 2000) yaitu, subsistem tata-nilai, sosial-ekonomi, artifact dan
subsistem bukan manusia, dalam rekonstruksi nilai-nilai sosial industrial. Menurut
pemahaman ini, sofistikasi rekayasa dan teknologi merupakan unsur amat penting,
sebagai indikasi internal sistem sosiokultural maupun stimulan industrialisasi. Akan
tetapi, sofistikasi adalah tool perubahan dan bukan yang terpenting seperti
disalahpahami selama ini sebagai penentu dan indikasi tunggal, bahkan sampai
penyetaraan bahwa industrialisasi adalah TIK dan kedirgantaraan.
Keterpaduan terapi ekonomi politik dan politik ekologi dalam pengembangan
industri bisa cermat dibangun untuk KkD melalui super-imposing beragam kaidah dalam
pengembangan kawasan (Maksum, 2007b). Pada tingkat pertama, keterpaduan bisa
dibangun dalam triangulasi sinergi antara: (i) pilihan intervensi strategis, politisekonomis-
sosial-teknologis-ekologis; (ii) keseimbangan sistem sosio-kultural yang
meliputi subsistem: tatanilai-sosial-artifact-nonhuman; dan (iii) tujuan pembangunan
kawasan pedesaan: growth-equity-sustainability (Maksum, 1997).
Pilihan strategis untuk KkD dengan demikian akan memiliki kesesuaian lokal dan
tidak menimbulkan lompatan budaya (cultural jumps), sekaligus bisa
mempersembahkan ketercapaian tujuan pembangunan: pertumbuhan, keadilan, dan
keberlanjutan. Dalam konteks inilah telaah partisipatif seksama untuk bisa memetakan
watak sistem sosiokultural yang sangat lokalistis dengan kepakaran dan kearifannya
semakin memiliki relevansi.
Pada tingkat kedua, berbasis pada keterbukaan jalan KkD, dalam pengertian
komunitas, sektoral maupun teknologis, maka KkD sangatlah terbuka bagi investasi
eksternal yang meliputi upaya on-farm, off-farm dan non-farm, sepanjang
endogenisasinya memenuhi triangulasi kedua, yaitu sinergi antara: (i) triangulasi
pertama: intervensi strategis, sistem sosio-kultural, dan tujuan pembangunan; (ii)
jaminan business security triangle, berintikan: sustainable profit, social progress dan
environmental protection; dan (iii) harmoni relasi natural: profit-people-planet. Dua hal
terakhir, diadopsi dari Parker (2001), merupakan kisi-kisi business ethics berkenaan
dengan investasi di pedesaan yang justiciable.
Peringatan metodologis ini perlu dilontarkan karena perjalanan bangsa sudah kian
parsial dan makin menjauhi kiblat, melupakan aspek sosiokultural dan mutu lingkungan.
Dalam Structural adjustment, access reform dan penghapusan dikotomi ekonomis
adalah prasyarat utama bagi industrialisasi pedesaan, baik internal memenuhi triangulasi
pertama maupun investasi eksternal menurut triangulasi kedua. Melalui pendekatan
tersebut, nilai tambah, daya beli publik, kinerja penanggulangan kemiskinan,
keberlanjutan pembangunan pertanian dan bangsa bisa ditingkatkan lebih memadai.
Pada gilirannya, kesenjangan desa-kota, antar-kelas, antar-sektor, dan antar-daerah bisa
ditekan, tidak justru membiarkan pedesaan dan daerah-daerah yang sudah tertinggal,
makin tertinggal dan ditinggalkan oleh pembangunan.
Kisi-kisi dua triangulasi besar industrialisasi pedesaan itu mengamanatkan kaidah
mutakhir pengembangan kawasan yang semakin multidimensi sebagai realitas tantangan
bersama yang dihadapi oleh Jurusan Teknologi Industri Pertanian (JTIP-FTP), Pusat
Studi Pedesaan dan Kawasan, dan Fakultas Teknologi Pertanian pada khususnya, serta
seluruh kekuatan akademik UGM pada umumnya, ketika masih meyakini dirinya
sebagai universitas ndesa dan motor penggerak pembangunan pedesaan.
Akhirnya, mari buka mata, betapa pas-pasan daya tawar politis sektor pertanian
sehingga segalanya ditentukan pihak lain, yang belum pernah melihat pohon nasi dan
pohon tempe, yang bisanya hanya menempatkan pertanian sebagai pelayan dan
kewenangan pilihan. Sudah waktunya aktifis pertanian tampil ke tengah, berdendang
tembang nelangsaning kawula alit, sebagai penentu keputusan dan arah perekonomian
yang agro-industrial, sekaligus melandasi rekonstruksi perekonomian nasional. Sekali
lagi, sudah bukan waktunya menghibur rakyat dengan pemanjaan legal belaka seperti
GBHN, Repelita, Propenas dan Propeda, yang tanpa gigi dan realisasi, termasuk pula
janji RPPK, jikalau revitalisasi pertanian tidak segera terealisasi..... na’udzubillah
Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 30 Januari 2008
Di Yogyakarta
Oleh:
Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, MSc
Selasa, 21 Oktober 2008
Menggunakan Softwere Easy Sample untuk mendapatkan ukuran sampel
Hasil penelitian dan analisis kita terhadap 50 petani sampel tadi, bukan untuk menggambarkan keadaan sosial-ekonomi mereka saja, tetapi adalah untuk menggambarkan keadaan sosial-ekonomi dari 300 petani (populasi). Lalu, bagaimana kita yakin bahwa gambaran dari 50 petani bisa mewakili keadaan 300 petani ? Jawabnya adalah: perlu teknik yang tepat dalam pengambilan sampel, dalam mengambil data dari sampel, dalam menentukan banyaknya (ukuran) sampel dan dalam analisis serta penaksiran data.
Dalam konteks menentukan berapa banyak sampel yang harus diambil, ada software yang cukup sederhana dan praktis dalam perhitungannya, yaitu Program EasySample. Selain bisa menentukan ukuran sampel, program ini juga bisa menghitung confidence level (tingkat kepercayaan) dari sampel acak kita dan menghitung probabilitas, menemukan error dari sampel. Ada juga fasilitas statistik sederhana seperti menghitung jumlah,rata-rata, standar deviasi, dan fasilitas untuk mendapatkan angka random yang berguna untuk memilih sampel.
Di bawah ini saya contohkan cara kerjanya.
Tampilan awal program EasySample adalah seperti berikut:
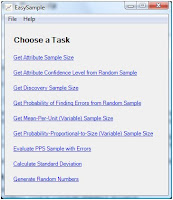
Ada 9 pilihan yang bisa diambil. Untuk menentukan ukuran sampel maka kita ambil pilihan pertama. Ketika pilihan pertama diklik, akan muncul tampilan berikut:
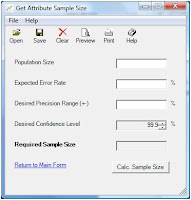
Pada pilihan ini kita diminta untuk memasukkan data mengenai jumlah populasi, tingkat kesalahan yang diharapkan, range dari tingkat ketelitian/ketepatan serta tingkat kepercayaan yang diinginkan. Katakanlah populasi kita 300 orang, tingkat kesalahan yang diharapkan 5 %, range tingkat ketelitian 10% dan tingkat kepercayaan 99,9 persen. Setelah memasukkan angka-angka tersebut klik Calc.Sample Size, maka akan didapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 44 orang (43,904) seperti tampilan berikut:

Dengan menggunakan program ini kita dapat lebih akurat dan memiliki latar belakang metoda pengambilan sampel yang dapat di benarkan secara statistik
Anda tertarik dengan program ini ? Silakan download disini.
Disadur dari Blog Junaidi FE-UNJA